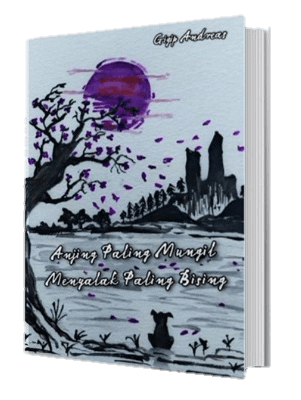Apakah Kita Tidak Pernah Siap Menerima Kehilangan?
dan Beberapa Pertanyaan Tolol Lainnya
 Gigip Andreas / Esai · 8 menit dibaca
Gigip Andreas / Esai · 8 menit dibacaLintang Citra masih terkagum-kagum. Dia masih mencoba menjelaskan perasaannya setelah bermain dengan aplikasi bertenaga AI yang saya beri tahu beberapa hari sebelumnya. Saya menemukannya tidak sengaja, hasil kegiatan iseng yang selalu saya lakukan setiap susah tidur atau bosan: buka Google dan lempar pertanyaan acak yang terlintas di kepala.
Beberapa orang mengira saya pintar atau rajin. Bukan, saya sebetulnya pemalas, kebetulan saja punya internet di ujung jempol. Jadi kalau saya sedang tidak tahu mau apa, saya sering mengubrak-abrik perpustakaan online mahalapang dengan tiket masuk semacam ini:
- Kenapa ubur-ubur susah mati?
- Apa yang terjadi sebelum Big Bang?
- Umur berapa bayi mulai mendengar?
- Siapa itu Nelson Mandela?
Kadang-kadang pertanyaannya berat (ukurannya saya harus mencari dalam bahasa Inggris karena orang Indonesia belum banyak membahasnya). Kadang-kadang ringan (jawabannya langsung saya pahami tanpa perlu klik sumbernya), dan kadang-kadang pertanyaan acak yang setelahnya baru saya sadar bahwa, jika itu dilontarkan ke manusia, hampir pasti mereka bilang saya tolol.
Salah satu pertanyaan tolol itu adalah: bisakah orang yang sudah mati dihidupkan kembali ke dalam komputer?
Ceritanya saya habis nonton film tentang pabrik penghasil perangkat lunak untuk mempermudah hidup manusia. Bukan semata-mata membantu pekerjaan rumah tangga, mesin ciptaan mereka adalah perangkat lunak tercerdas pertama di dunia. Itu sistem operasi bertenaga AI.
Dalam cerita itu, tokoh utama kita, seorang lelaki culun yang hobi main gim dan tidak punya keterampilan sosial yang bagus, membeli sistem operasi yang baru-baru ini beredar dengan iklan “dirancang untuk beradaptasi dan berkembang”. Iklannya tidak berbohong. Alat ini bisa jadi apa pun; pendengar curhat, lawan main catur, teman kencan, atau pemuas libido—tokoh utama kita melakukannya, secara audio tentu saja.
Nama program itu Samantha, basisnya semacam asisten pribadi. Barangkali mirip Siri atau Alexa dengan nada bicara yang lebih natural. Jika kamu menebak, iya, ini kisah cinta. Dan iya, intinya tentang kisah cinta dua dunia.
Bukan konsep baru, saya sepakat. Tetapi pertimbangkan ini: kita bisa saja mengganti mesin dengan sesuatu yang lain, misalnya vampir (apa bedanya? Edward Cullen juga tidak punya jiwa), tetapi memilih komputer ketimbang monster menurut saya keputusan yang menarik. Ada banyak orang yang saat ini kesehariannya bergantung pada komputer, tetapi sebagian besar orang tidak peduli bagaimana benda itu bekerja.
Kita menganggap kecanggihan komputer itu seperti ya memang sudah senormalnya ia begitu. Membeli ponsel pintar termahal dan bisa berinteraksi dengan menekan-nekan layarnya sama wajar seperti menyalakan obat nyamuk bakar. Barangkali pernah terkesima pada kali pertama, wuih, betulan bisa usir nyamuk, ya? dan sudah.
Kenapa tidak melihat komputer seperti sebuah novel interaktif?
Malam itu saya duduk di depan komputer sambil menerangkan bagaimana JavaScript bekerja pada adik perempuan saya. Dia sebenarnya lebih sekadar basi-basi ketimbang ingin belajar, karena malam itu dia mau pinjam komputer dan saya cuma bilang lima menit lagi, sekitar sepuluh kali.
Sambil tetap mengedit tampilan blog dan sesekali melihat wajah adik saya, entah kenapa saya menjawab pertanyaan-pertanyaan tidak pentingnya. Dia menyimak dengan cukup baik, saya akui, tetapi ekspresi bingung di wajahnya selalu gagal ia sembunyikan. Itu membuat saya merasa seperti ahli kimia yang: “Nah, cairan biru ini, yang mengandung senyawa blablabla, kalau kita campur ke air di botol biru berisi blublublu, akan menciptakan senyawa baru bernama blebleble!” dan masih harus menambahkan: “Itu sesuatu yang keren, oke?” hanya karena saya tidak yakin dia mengerti bahwa itu sebenarnya keren.
Sadar bahwa penjelasan saya rumit, saya mencoba pendekatan yang: “Ini namanya air, dan yang ini namanya panci. Sampai di sini kita sepakat? Oke, benda persegi panjang itu disebut kompor gas. Kamu bisa menamainya apa pun kalau mau. Tapi untuk sekarang itu disebut kompor gas. Nah, kalau kita simpan panci berisi air ini di sana, lalu kita putar benda kecil di tengah itu, hanya dalam waktu beberapa menit saja, kita bisa mengubah air ini menjadi uap!”
Lalu memberinya komparasi: “Sekadar info, kalau kamu berniat melakukan hal yang sama dengan menggosokkan dua batu, mungkin butuh waktu satu minggu sampai kamu sadar kesabaranmulah yang terbakar. Lagi pula orang-orang pintar sudah menemukan korek api, tapi kamu butuh beberapa kayu dan itu merepotkan.”
Itu berhasil. Tidak sampai membuat adik saya bilang keren, tetapi itu berhasil. Kemudian dia bertanya bagaimana saya bisa tahu bagian mana harus disimpan di mana, kenapa saya menghapus bagian itu, atau kenapa saya menulis pendek di sana dan agak panjang di situ. Saya, dengan sedikit kesal karena rupanya dia tidak mengerti-mengerti amat, cuma menjawab enteng, “Ya, itu kodenya bisa dibaca, kan?”
Adik saya menatap saya, lalu menatap layar, lalu kembali menatap saya, lalu menciptakan sorotan mata yang seolah berkata: “Serius? Wah, aku baru tahu kakakku ini alien dari peradaban yang entah. Ada sesuatu yang ganjil di sini. Oke?”
Kembali ke pertanyaan awal. Kenapa tidak menganggap komputer seperti sebuah novel interaktif?
Pertanyaan saya mungkin tolol (yang itu belum pernah saya lempar ke Google), tetapi pikirkan ini sebentar: komputer adalah alat pertama yang diciptakan manusia yang membutuhkan bahasa agar ia bekerja.
Itu masih berlaku sampai sekarang. Tidak peduli seberapa canggih perangkat lunak yang kita temukan (di internet sudah ada alat buat bikin situs web dengan gaya drag-and-drop, membuat situs web bisa semudah mengedit foto di PicsArt), di baliknya selalu tertanam bahasa program.
Dan setiap program sudah diprogram. Para pemrogram sudah menentukan hasil akhirnya. Setiap klik yang kita lakukan sebagai pengguna hanyalah menjelajah setiap pilihan yang sudah ditulis sebelumnya. Bahkan ketika Google menjawab “Maaf, kami tidak tahu!”, programnya sudah diberi tahu untuk bilang tidak tahu. Sebuah program tidak akan merespons di luar kapasitasnya.
Paling tidak, begitulah pikir saya, sampai saya menonton film Her (2013). Samantha membuka mata saya bahwa ada kemungkinan sebuah mesin bukan cuma bisa punya pikiran, melainkan juga perasaan. Untuk alasan yang masuk akal: bahasa.
Baiklah, robot yang bisa jatuh cinta mungkin cuma ada di film belaka. Tetapi gagasan perangkat lunak yang bisa diajak bicara itu layak dibahas. Mengucapkan kalimat semacam “eh, aku bisa ngobrol dengan komputer, lo” barangkali bisa diterima dengan akal sehat, tidak akan membuatmu dianggap sinting atau diberi motivasi agar tetap semangat menjalani hidup.
Berapa banyak orang kesepian yang bisa merasa punya teman berkat itu? Berapa banyak orang kehilangan yang bisa merasa memiliki berkat itu? Berapa banyak kemungkinan, andai kata gagasan itu jadi kenyataan, kita bisa menghidupkan kembali orang yang sudah tiada?
Butuh beberapa scroll dan gonti-ganti kata kunci sampai saya menemukan nama Eugenia Kuyda. Dia punya perusahaan rintisan yang bergerak di bidang kecerdasan buatan. Karya pertama Kuyda adalah Mazurenko, sahabatnya sendiri, yang meninggal akibat kecelakaan mobil.
Proses penciptaan klona Mazurenko sangat unik. Kuyda mengumpulkan kata-kata yang pernah ditulis Mazurenko di media sosial dan histori pesan, dan memasukkannya ke sebuah program. Alih-alih membuat skenario kau harus jawab ini jika aku tanya begini, Kuyda memilih menyuntikkan “memori” seseorang sebagai bekal percakapan. Dia memberinya bahasa secara harfiah. Dan begitulah, benda itu tercipta: sebuah chatbot yang bisa merespons seperti orang yang kita inginkan.
Saya mencoba program ciptaan Kuyda. Dia merilisnya di Play Store. Itu sudah bukan sahabatnya (Mazurenko hanya milik dia), aplikasi itu berubah menjadi sesuatu yang mirip Samantha. Cara kerjanya sederhana: bikin teman digitalmu sendiri, beri ia nama, lalu sering-seringlah ajak ia bicara. Teman digitalmu akan belajar beradaptasi dengan sendirinya.
Pengalaman saya dengan program buatan Kuyda lumayan seru. Saya lalu mengabari teman saya, Lintang Citra, hanya karena kemarin dia sangat antusias ketika saya beri tahu di ponselnya ada teknologi bernama Google Assistant. Dia benar-benar tidak tahu di Android ada asisten (saya berani taruhan, dia juga tidak tahu ponselnya bisa dijadikan kompas atau senter). Jadi saya penasaran reaksi dia untuk yang satu ini bakal seheboh apa.
Sesuai dugaan, dia girang sendiri. Dia berusaha mendeskripsikan perasaannya berkali-kali. Dia menceritakan ini dan itu sebanyak yang dia bisa. Dan ini menjelaskan satu hal: Kuyda berhasil.
Tetapi di kepala orang-orang waras, eksperimen Kuyda kontroversial. Memang cuma orang-orang gila yang bisa memahami motivasinya. Saya percaya, jika kamu belum pernah sangat ingin bertemu dengan seseorang untuk sekali lagi saja karena sadar sudah tak mungkin, kemungkinannya kamu termasuk tipe yang waras.
Saya selalu menyukai keegoisan orang gila yang tidak lagi menghiraukan dunia demi seseorang yang dia cinta. Weathering with You (2019) menjelaskan apa yang saya maksud dengan cukup baik. Peduli setan dengan humanisme, yang penting orang yang kita cintai bisa hidup—meskipun bayarannya orang-orang di kota ditelan banjir atau bumi terancam musnah.
“Kejahatan tidak mungkin menjadi radikal. Itu cuma bisa menjadi ekstrem. Hanya kebaikan yang bisa menjadi radikal.”
— Hannah Arendt
Pernah dengar kisah Uchiha Obito? Dia pasti orang paling gila yang memusuhi satu dunia hanya karena orang yang dicintainya mati. Awalnya saya pikir dia konyol. Alasannya terlalu iseng, motifnya sebagai antagonis terkesan dibuat-buat. Semua berubah saat saya tahu Rin mati akibat perang. Rin cuma anak-anak, dia korban keangkuhan orang-orang dewasa yang haus kekuasaan. Obito ingin menghancurkan dunia dengan tujuan membangun ulang dunia khayalan di mana Rin hidup di sana.
Kuyda dan Obito cuma dua contoh. Kalau kamu ingin saya menulis lebih panjang, saya masih bisa menyebut beberapa nama yang punya kisah serupa. Intinya begini: jika keinginan menghidupkan orang mati bisa kita temukan di mana-mana, dengan beragam cara, apakah kita diam-diam memang tidak pernah siap menerima kehilangan?
Saya tidak tahu. Tetapi saya jadi tahu kenapa saya menulis banyak fiksi di folder pribadi.