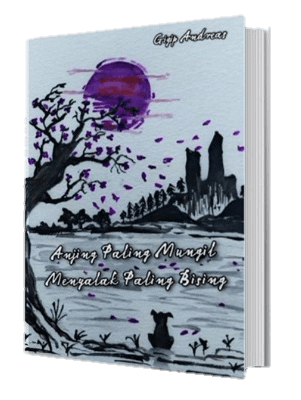Membaca dalam Gelap
 Gigip Andreas / Jurnal · 7 menit dibaca
Gigip Andreas / Jurnal · 7 menit dibacaKamu sangat suka membaca. Kamu bisa tahan duduk berjam-jam melahap halaman demi halaman, sering kali sampai abai memperhatikan hal-hal yang terjadi di luar. Kamu akan terus membaca dengan keras kepala meskipun matahari mulai memudar.
Ketika cahaya kian padam, matamu akan kian menyipit berusaha menangkap setiap kata, dan bukumu secara bertahap kian mendekat ke batang hidung. Pada titik tertentu seseorang akan mengetuk pintu kamarmu. Ia masuk dan mendapatkanmu sedang mengintip sambil membungkuk. Ia menekan sakelar.
“Kenapa kamu membaca dalam gelap? Itu bisa merusak matamu,” katanya.
Kamu hanya tersenyum dan mulai sadar bahwa sekarang jadi jauh lebih mudah untuk membaca.
Pada hari lain, kamu bisa menghabiskan beberapa buku dalam sehari. Kamu adalah pembaca yang hebat. Dan kamu senang menceritakan ulang buku-buku yang sudah kamu baca ke internet, biasanya dalam bentuk ulasan di sebuah blog. Orang-orang menyukainya.
Pada lain hari, kamu tiba-tiba kembali kesulitan membaca entah kenapa. Kamu tidak berhasil mencapai setengahnya, bahkan sudah tersendat-sendat di awal-awal. Kamu memberi tahu teman-temanmu dan mereka bilang mungkin bukunya salah. Mereka lalu menyebutkan beberapa judul yang menurut mereka pasti berhasil.
Kamu mencobanya, dengan susah payah tentu saja, dan berujung nihil. Buku-buku itu tetap tidak bisa dibaca. Kamu bahkan lupa bagaimana rasanya membaca. Orang-orang mulai berkata sepertinya kamu tidak bisa membaca karena yang lain berhasil membacanya dan kamu jawab tidak. Tetapi pada akhirnya semua orang pergi mencari pencerita lain, dan kamu hanya bisa termangu di atas kasurmu dengan kepala menunduk sambil sibuk mempertanyakan berbagai kenapa.
Kamu tahu kenapa?
Karena kamu tidak sadar matahari sudah lama terbenam sementara tidak ada yang kunjung datang untuk menekan sakelar. Dan sejak hari itu kamu takut tidak ada lagi yang akan menekan sakelar, takut tidak ada lagi yang akan membantumu menyalakan lampu kamar.
Ada satu monolog Flint Lockwood yang menempel di kepala saya sejak pertama kali menonton Cloudy with a Chance of Meatballs, ketika Flint dirundung oleh teman-temannya di sekolah: aku ingin kabur saja hari itu, tapi kau tidak bisa melarikan diri dari kakimu sendiri.
Andai bisa memilih, saya juga ingin kabur dari semua rasa takut yang menyelimuti saya akhir-akhir ini, tetapi Flint benar.
Satu bulan yang lalu saya kecelakaan. Belum masuk kategori gawat tetapi cukup untuk membuat saya khawatir: kedua lutut saya cedera, kulitnya sobek dan sering terasa ngilu bahkan dalam posisi kaki lurus.
Saya bisa mengingat dengan jelas bagaimana saya terlempar ke jalan. Setelah terpental dari motor, saya berkali-kali terguling di aspal, dan saya mendengar beberapa teriakan ibu-ibu (yang belakangan saya tahu ternyata pedagang warung kopi di Zona Merah Sukajadi).
Saya dibantu berdiri dan dituntun oleh sopir Grab. Dia berulang kali bertanya bagian tubuh mana yang terasa sakit, sambil terus-menerus menghubungi satu per satu teman-temannya untuk membawakan P3K.
Anehnya, saat itu saya tidak merasa sakit. Ada beberapa perih, tetapi saya sangat yakin saya masih bisa berdiri. Jadi saya menolak tawaran orang-orang yang ingin mengantar saya pulang karena saya tidak mau merepotkan mereka lebih jauh. Lebih-lebih, saya sebenarnya mau jemput pacar pulang kerja. Agak tidak lucu jika akhirnya kami sama-sama dibonceng orang lain.
Keanehan yang kedua, saya benar-benar bisa menjemput pacar. Saya bisa mengantarnya pulang (meskipun dia agak marah karena menunggu lama), dan saya juga bisa pulang, bahkan bisa jalan ke kamar (meskipun dengan sedikit pincang karena masih terasa perih). Saya baru mulai merasa pusing setelah tiba di kamar. Malam itu saya langsung tidur.
“Kemarin pulang jam berapa?”
Ibu saya tanya karena ia pulang pukul dua belas dan tidak melihat motor saya. Ditambah lagi kamar saya terpisah dari rumah, kamar saya bekas gudang di halaman belakang.
Saya jawab sekenanya karena saya sendiri tidak tahu. Mungkin pukul setengah satu.
“Terus kenapa bisa gini?”
Saya tidak menjawab.
Usai membasuh luka saya dengan air hangat campur garam, ibu menaburkan bubuk kopi ke dagu saya di sebelah kiri dan lutut di kedua kaki. Saya juga baru tahu bubuk kopi bisa meredam luka.
Awalnya saya pikir saya akan cepat sembuh. Saya pikir semuanya akan baik-baik saja. Saya pikir ini cuma luka kecil yang wajar, luka kecil yang bisa saya tahan selama beberapa hari. Sampai akhirnya dua minggu telah berlalu dan saya masih berbaring di atas kasur. Ibuprofen sudah habis. Paracetamol sudah habis. Kenapa saya masih tidak bisa berdiri?
Lama-lama, saya mulai terbiasa dengan tidur tanpa selimut dan kaki yang tidak bisa ditekuk. Saya mulai terbiasa dengan tiba-tiba panas saat terbangun. Saya mulai terbiasa memegang dinding sambil menjinjitkan kaki kiri ketika ingin ke kamar mandi. Saya mulai terbiasa melamun di sepertiga malam hingga menjelang pagi.
Saya tidak ingat pada malam ke berapa saya berhenti bertanya, barangkali bertepatan dengan saya berhenti berdoa.
Saya mulai putus asa.
Masalahnya bukan saya tidak rela jika tidak bisa berjalan lagi. Masalahnya, saya takut ketika saya tidak bisa mengandalkan diri sendiri untuk melakukan sesuatu, harus bergantung pada orang lain, tetapi tidak ada orang di sana.
Saya takut sendirian.
Saya takut orang-orang mulai meninggalkan saya ketika saya perlahan rusak, tidak berfungsi sebagaimana mestinya, tidak seprima sediakala.
Saya takut tidak ada orang yang akan menekan sakelar ketika saya kesusahan membaca di tempat gelap. Saya takut lampu kamar saya redup selamanya.
Satu bulan telah berlalu.
Saya mulai bisa berdiri tegak, meskipun hanya mampu bertahan kurang dari lima menit. Saya harus terus berjalan jika ingin tetap berdiri. Setiap kali saya berhenti, lutut saya akan seperti kesemutan dan saya harus duduk atau berjalan lagi.
Adapun yang saya syukuri dari jatuh sakit kemarin, saya jadi punya lebih banyak waktu senggang untuk berpikir dan merenung. Salah satunya tentang ibu.
Bisa dibilang, hubungan saya dengan ibu agak canggung. Dekat dan jauh. Kukuh dan rapuh. Abai dan acuh. Sesekali saya merasa ikatan emosional kami seperti mainan jepret karet. Itu rentan putus jika ditarik terlalu kuat, tetapi juga tidak akan melesat jika terlalu pelan.
Sebenarnya, saya yang membuat jarak, meskipun saya juga tidak jelas untuk apa dan kenapa. Mungkin cuma ego yang tidak ingin terus-menerus diperlakukan seperti bocah, semacam mencari pembuktian bahwa saya sudah dewasa.
Saya ingat, Juli tahun lalu, sebelum saya berangkat ke luar kota, ibu menitip pesan panjang lebar tentang jaga diri dan saya cuma mengatakan ini:
Jangan samain aku sama Tsaqif atau Nasywa. Aku bukan anak kecil lagi.
Saya menyesal.
Selama dua minggu lebih saya sakit, ibu yang selalu mengantarkan makanan ke kamar saya. Ia juga yang menyeka badan saya. Ia juga yang membasuh luka saya. Ia juga yang paling sering bertanya gimana kakinya?
Saya sedih dan malu, karena rupanya orang yang saya beri dinding adalah orang yang paling sabar merawat saya. Bahwa ternyata orang yang ingin saya tunjukkan “saya bisa berdiri sendiri” adalah orang yang selalu membantu saya berjalan. Dan ia akan melakukannya tanpa perlu menunggu saya meminta tolong.
Sepertinya semua orang boleh sakit kecuali ibu. Karena jika ibu yang sakit, belum tentu saya sanggup seperti ibu ketika saya yang sakit.
Sebelum bisa berdamai, saya kesusahan menyelesaikan ini. Tulisan ini saya buat selama seminggu karena rasanya sangat berat untuk menceritakan sisi lemahmu ke banyak orang.
Tetapi, sulitnya memahami kesedihan, ketakutan, dan rasa sakit orang lain adalah gajah di dalam ruangan. Itu masalah yang terlampau besar sampai-sampai kita tidak sadar bahwa itu adalah masalah.
Jadi saya memutuskan untuk tetap menulis ini, untuk siapa pun yang sedang berjuang membaca dalam gelap. Mohon jangan terlalu keras pada diri sendiri. Itu bukan salahmu. Tidak apa-apa untuk menyimpan bukunya sejenak dan lihat apakah kamu bisa meraih sakelar.
Hal lain yang belakangan saya sadari: saya sudah lama selalu merasa sendiri karena mungkin saya selalu mencoba melakukan segala hal sendiri. Saya selalu berusaha menanggung semua beban saya sendiri. Mungkin sebenarnya, akan ada satu dua yang suka rela membantu saya, seandainya saya bersuara.
Jika kamu butuh seseorang untuk bercerita, jangan sungkan mengirimi saya surel. Saya di sini dan akan selalu senang diajak bicara.