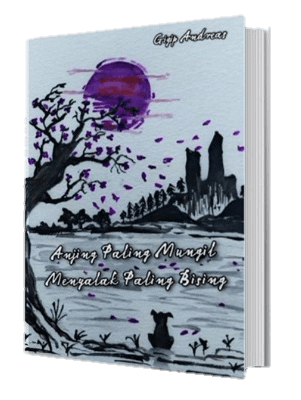You Said I Deserve Someone Better
 Gigip Andreas / Jurnal · 12 menit dibaca
Gigip Andreas / Jurnal · 12 menit dibacaDi ruang tamu. Pukul satu tengah malam. Hanya ada aku dan ibu. Aku sedang merokok sambil main ponsel, menggulir beranda media sosial, saat ibu tiba-tiba menanyakan kabarmu.
Aku terdiam cukup lama, hanya mengisap rokok, tanpa mengalihkan pandanganku dari ponsel. Tangan kiriku masih menggulir-gulir layar tapi aku tidak membaca apa-apa. Aku hanya mengulur waktu untuk menyusun kata-kata.
“Baik,” jawabku, berbohong lagi, kesekian kalinya. Aku tidak tahu kabarmu. Kita sudah lama berpisah. Kita sudah lama tidak berkomunikasi. Dan aku tidak pernah mencari tahu kabarmu.
“Tapi kalian masih baik-baik?”
Selama ini aku selalu berbohong pada ibu. Aku selalu bilang kita baik-baik saja, dan aku selalu bilang kabarmu baik tapi kamu sibuk bekerja, makanya tidak ada waktu untuk mampir ke rumah. Sesekali aku pergi ke luar dan bilang untuk menemuimu, agar ibu yakin kita baik-baik saja. Meskipun sebenarnya aku pergi ke tempat temanku, atau aku hanya ke Indomaret dan merokok.
Aku tidak pernah menceritakan hal-hal buruk tentangmu pada ibu. Aku tidak cerita ketika kita bertengkar, aku tidak cerita ketika kamu membuat masalah. Selama ini ibu hanya tahu hal-hal baik tentangmu. Selama ini aku hanya cerita hal-hal baik tentang kita.
Aku selalu berpikir kita bisa bersama. Ya, kita sering bertengkar, beberapa kali memutuskan berpisah, tapi pada akhirnya kita bicara dan baikan. Jadi aku selalu berpikir, saat kita bertengkar atau berpisah, kita hanya butuh waktu untuk masing-masing, sebelum akhirnya kita bisa bicara dan baikan lagi. Tapi kata-kata terakhirmu membuatku berpikir situasi yang sekarang berbeda. Aku mulai berpikir kamu benar-benar ingin mengakhiri semuanya.
“Sebenarnya, udah lama pisah.”
Aku menarik napas panjang. Rasanya berat sekali mengatakan itu. Aku tahu ibu menyukaimu, aku tahu betapa dia menyayangimu.
Aku tidak berani melihat ibu. Tapi aku bisa merasakan dia terkejut. Nada bicaranya agak naik saat dia bertanya. Tanpa kusadari, nada bicaraku juga agak naik saat bicara, lalu suaraku menjadi terbata-bata, dan aku memalingkan wajahku sambil menatap lampu. Aku tidak ingin menangis di depan ibu.
“Apa kabar?” tanyamu. “Maaf ini terlalu lama. Aku gak tahu kita bakal kayak gini terus sampai kapan. Aku gak mau bikin kamu kesiksa dengan sikap seenaknya aku. Aku mau mundur aja kayaknya.”
Hari itu aku mengiyakan. Aku hanya tidak tahu harus merespons apa. Kamu datang setelah menghilang setengah tahun. Kamu minta break, yang aku artikan kamu butuh ruang dan waktu. Tapi kamu datang untuk mengucapkan perpisahan. Semuanya terasa canggung, terasa terlalu tiba-tiba, aku tidak tahu harus mengatakan apa selain iya.
“Makasih banyak buat semuanya. Gak akan pernah aku lupain. Aku cuma gak tahu harus gimana lagi biar kita bisa jalan terus, sisi lain aku juga gak mau nyiksa kamu terus-terusan. Makasih, makasih yang sebesar-besarnya untuk waktu bersamanya, walau gak banyak hal-hal manis bisa aku kasih buat kamu. Aku minta maaf udah banyak lakuin salah, nyakitin kamu terus-terusan. Maaf, maaf yang sebesar-besarnya. Aku berharap kita bisa ketemu lagi dengan versi kita yang seterbaik mungkin. Sampai kapan pun kamu tetap yang terbaik.”
Semua kata-katamu membuat kepalaku beku. Aku tidak bisa berpikir. Aku butuh waktu untuk memproses kalimatmu. Tapi aku tidak punya waktu untuk hanya diam.
Jadi kuucapkan terima kasih, lalu kuceritakan tentang mimpiku, dan aku meracau tentang tidak perlu meminta maaf, jika ingin pergi tinggal pergi, dan kudoakan jika kita tidak berhubungan lagi semoga hidupmu jauh lebih baik daripada ketika kamu bersamaku.
Kurasa aku bisa merasakan apa yang kamu rasakan saat itu. Perasaan sedih, berat, pilu. Tapi aku tidak tahu apa isi pikiranmu. Kamu hanya bilang, “Kalau jodoh gak akan ke mana, kan?”
Mungkin, atau entahlah. Hari itu sebenarnya aku ingin bertanya, apa yang kamu maksud dengan jodoh. Apakah kamu hanya mencemaskan ibuku yang selama ini selalu menilaimu baik dan telanjur menaruh harapannya padamu? Atau itu sebatas kalimat penghibur agar perpisahan kita tidak terasa terlalu menyedihkan? Atau kamu memberi pesan ada kemungkinan kita akan bersama lagi, seperti suatu hari nanti kamu mungkin berubah pikiran dan kembali?
Yang mana pun, yang terakhir terdengar ide yang buruk. Kurasa kita menjadi teman saja. Atau mungkin tidak perlu berteman sama sekali, kurasa aku tidak ingin kamu kembali. Kurasa aku tidak ingin kita menjadi sesuatu yang kita bayangkan pada saat-saat kita bahagia. Kurasa aku tidak ingin melihatmu lagi. Kurasa lebih baik kita tidak perlu berbicara lagi. Kamu meninggalkanku dengan cara yang membuatku merasa seperti orang yang tidak diinginkan. Kamu menghindariku dengan cara yang membuatku akan selalu mengenangmu dengan perasaan bersalah. Kemungkinan macam apa yang membuatmu bisa bilang kalau jodoh gak akan ke mana, sedangkan kamu sendiri yang bersikeras kita tidak bisa lagi bersama?
Aku hanya tidak mengerti. Aku tidak tahu apa yang ada di kepalamu. Aku merasa ada hal-hal yang kamu sembunyikan dariku, hal-hal yang enggan kamu katakan padaku. Dan jika itu benar, sebenarnya, itu hanya memperburuk semuanya.
“Bisa cerita?” tanya ibu. Dia ingin aku menjelaskan semua yang terjadi karena dia tidak mengerti. “Ya, gak apa-apa kalau kamu gak mau cerita kejelekan dia. Ibu ngerti, kamu juga pernah bilang, kejelekan pasanganmu cukup kamu yang tahu, orang lain gak perlu. Ibu hargai itu. Ibu cuma mau tahu, gimana ceritanya kalian udahan. Gimana awalnya, apa yang terjadi, selama ini kamu gak pernah cerita apa-apa.”
Aku menatapnya. Ibu cuma tersenyum. Dia berdiri dari kursinya, beralih ke kursi di sebelahku. Dia menepuk pundakku.
Air mataku jatuh. Aku membiarkan tubuhku rubuh di senderan kursi. Ibu mengusap-usap pelan punggung tanganku. “Apa yang terjadi, biar terjadi. Mungkin memang udah harus jalannya. Ibu gak akan hubungin dia buat tanya-tanya, Ibu cuma mau dengar dari kamu. Kalaupun nanti kalian baikan, ya, Ibu bakal pura-pura gak tahu tentang ini. Gak akan mengubah pandangan Ibu ke dia, menurut Ibu dia anak baik, mau nemenin kamu cukup lama. Ibu cuma mau tahu, kenapa kalian harus udahan.”
Aku menarik napas dalam-dalam. Aku menyeka air mataku, menyalakan rokok baru, dan aku mulai bercerita. Kali ini nada bicaraku lebih teratur.
“Waktu itu kamu minta break, kenapa?”
“Aku minta break karena aku pengin minta waktu buat berpikir aja, aku ini masih bisa gak lanjutin hubungan sama kamu? Apakah worth it atau malah jadi nambah beban? Aku minta break itu lebih ke ingin tahu gimana perasaan aku ke kamu saat itu, juga ke depannya.”
Aku artikan itu kamu ingin mencoba melihat situasi tanpa hadirku. Seperti bagaimana hidupmu berjalan jika aku tidak ada. Bagaimana hari-harimu berlalu ketika kita sudah tidak komunikasi. Apakah kamu akan sanggup? Atau aku malah memenuhi kepalamu? Kuanggap itu sebagai pencarianmu, dan sepertinya jawaban yang kamu temukan adalah kamu bisa melewati semuanya.
Jujur saja itu egois. Pada masa-masa pencarianmu, kamu mungkin berusaha mencari tahu apakah kamu bisa jalani hari-harimu tanpa hadirku. Tapi pernahkah kamu memikirkan posisiku? Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana caraku jalani hari tanpa hadirmu? Pernahkah kamu penasaran, apa yang aku lakukan ketika aku membutuhkanmu tapi tidak bisa menghubungimu? Tidakkah kamu ingin tahu sesesak apa perasaanku ketika jariku refleks menekan kontakmu lalu urung dan akhirnya kutelan semuanya sendirian?
“Dan apa yang kamu rasain? Apa kesimpulan kamu sampai akhirnya pilih mundur?”
“Yang aku rasa ya udah gak bisa aja? Gak bisa karena siklusnya seperti ini terus. Di saat kamu udah mau berubah, aku udah gak mau. Gak akan bisa. Sayangnya aku, mungkin kamu juga, udah bukan soal say i love you. Udah lebih dari itu. Dan menurutku, kemarin milih mundur juga itu bentuk sayang aku sama kamu.”
Lucu. Dari mana pemikiran itu bisa muncul di kepalamu? Bagaimana kamu yakin meninggalkanku akan membuatku lebih bahagia? Kenapa kamu tidak terpikir, meninggalkanku malah membuatku semakin sedih? Meninggalkanku malah membuatku semakin tersiksa? Tapi aku lebih penasaran pada hal lain, jadi aku memilih bertanya, “Waktu itu yang ada di pikiran aku, tentang kamu gak tahu harus gimana lagi karena kamu merasa kamu cuma nyiksa aku, apa itu nyakitin kamu?”
“Iya. Itu nyakitin aku, apalagi bayangin kamu yang udah mau berubah tapi aku tutup mata. Makanya aku pilih mundur.”
“Dan setelah kamu mundur, setelah semua ini, kamu bahagia?”
“Bahagia menurutku belum ya. Cuma lebih ke tenang aja. Tenang pikiran.”
Aku sangat sakit hati malam itu. Ternyata selama ini aku cuma beban pikiran untukmu. Ternyata kamu merasa lebih baik tanpa adanya aku. Ternyata pikiranmu lebih tenang saat aku dan kamu tidak lagi menjadi kita. Apa sebenarnya arti aku untukmu? Apanya yang kamu tetap yang terbaik, ketika aku hanya penyebab masalah untukmu, ketika aku adalah orang yang mengacaukan pikiranmu?
Aku tidak ingin berdebat atau bertengkar. Aku hanya ingin kamu mengerti bahwa semua ini menyakitiku. Jadi aku mengalah, dan kubilang betapa naifnya aku.
“Emang kamu gak ngerasa capek sama sikap aku? Gak pusing? Emang kamu gak bosan tiap bilang bisa perbaiki atau mau memperbaiki tapi akhirnya selalu gitu-gitu lagi? Apa kamu gak ngerasa seperti gak diihargai sebagai cowok? Kamu gak naif. Aku juga pernah, kok, di fase kayak kamu sebutin tadi. Kamu mau sejatuh apa pun, aku terima. Aku maunya sama kamu. Tapi lama-lama aku pikir gak adil juga rasanya kalau aku terima kamu, dan aku paksa kamu buat nerimain aku juga, dengan segala keribetan yang aku punya.”
Aku mulai berpikir kata-katamu adalah sindiran. Apakah sebenarnya selama ini kamu lelah dengan sikapku? Pusing dengan kelakuanku? Bosan dengan setiap obrolan memperbaiki hubungan kita? Apa kamu merasa tidak dihargai sebagai perempuan, karena aku laki-laki yang terlambat sadar? Karena aku laki-laki yang lambat dalam belajar? Karena aku baru mengerti hal-hal setelah kamu merasa lelah, pusing, dan bosan?
“Entah, sih, ya,” kataku pada ibu, “enggak ngerti juga. Tapi, yang kepikiran, sih, dia kayak bilang, waktu dan kesempatan yang aku kasih udah habis, kamu terlalu lama, lambat, jadi dia pilih pergi.”
Ibu hanya mengangguk pelan seolah-olah dia memahami semua yang kukatakan, meskipun aku yakin dia masih punya sejuta pertanyaan. “Ya, kalau memang gitu, ya, udah, terima aja. Dia berhak dapetin yang lebih baik dari kamu. Kamu enggak merasa kamu satu-satunya yang terbaik buat dia, kan? Kamu enggak merasa cuma kamu yang bisa ngasih yang terbaik buat dia, kan?”
Aku mengangguk.
“Ya, ya, udah. Gak apa-apa, kalau memang harus pisah. Kalau ini memang yang terbaik buat kalian.”
Aku mengangguk lagi.
“Kamu gak akan tidur? Mau bikin kopi lagi?”
“Bisa sendiri.”
Aku berdiri dan berjalan ke arah dapur. Ibu masih duduk di tempatnya.
“Tapi, kamu, masih sayang sama dia?”
Ada hari-hari ketika aku ingin tahu kabarmu, tapi enggan menyapa karena kurasa kita memang tidak perlu bicara lagi. Biasanya aku akan mengalihkan pikiranku dengan apa pun, membersihkan rumah, pergi ke rumah teman dan numpang menginap hanya untuk mendengarkan mereka bercerita, bermain gim, membuat situs web acak dengan alat-alat yang aku tidak akrab, menonton YouTube, membaca buku. Hingga satu waktu, aku merasa sudah bisa berdamai, jadi aku membuka profil akun Instagram-mu, setelah lama tidak.
Aku melihat Instagram Story yang kamu unggah. Kamu pulang kerja, mampir ke suatu tempat bersama teman-temanmu. Badanmu terlihat kurus. Wajahmu agak kumal, matamu lelah. Kenapa kamu tidak terlihat lebih bahagia? Kenapa berat badanmu turun? Kenapa kamu seperti sedang banyak pikiran?
Aku juga melihat-lihat beberapa foto yang kamu unggah di feed. Ada satu foto yang membuatku termenung cukup lama. Kamu mengambil swafoto, duduk berdua dengan laki-laki di atap di suatu tempat, malam-malam, tanganmu merangkul bahu laki-laki itu dan dia menyandarkan kepalanya ke dadamu. Mulanya kukira dia pacar barumu. Lalu aku ingat wajah itu, dia rekan kerjamu. Setidaknya dahulu kalian teman, mungkin kini pacar, entahlah.
Aku tidak mempermasalahkan hubungan kalian. Bahkan jika lelaki itu seseorang yang tidak kukenal dan dia memang pacar barumu, aku tidak peduli juga. Hanya saja, melihat foto itu, aku memikirkan hal-hal lain.
Kamu tidak pernah mau mengunggah fotoku, bahkan setelah aku memintanya. Kamu selalu beralasan sampai aku merasa itu tidak perlu lagi. Tapi jarak sebentar kamu meninggalkanku, kamu mengunggah foto bersama laki-laki lain. Aku hanya penasaran, seburuk apa aku bagimu sampai untuk waktu sekian lama menjadi pacar sangat sulit meminta sekadar fotoku diunggah, sedangkan orang lain (yang mungkin hanya teman), bisa semudah itu, dengan pose seintim itu?
“You deserve more more and more better than me. From all the childish things I had, all the disaster I made.”
Hari ketika kamu bilang aku layak mendapatkan seseorang yang lebih baik, aku bertanya-tanya kenapa kamu tidak mau menjadi orang yang lebih baik? Atau, kenapa kita tidak bisa tetap bersama dan sama-sama membuat semuanya menjadi lebih baik? Atau kamu hanya tidak mau menjadi lebih baik untukku, tapi bersedia untuk orang lain?
Kuakui, aku juga banyak salah. Banyak sekali melakukan kebodohan. Terutama karena kita menjadi pasangan ketika masih bocah, dan aku memang bocah arogan. Ya, aku tidak main tangan, aku tidak pernah melakukan kekerasan fisik, tapi teramat banyak aku melontarkan kata-kata kasar, menggoreskan kalimat-kalimat pedih yang melekat di hatimu. Sering kali aku hanya memikirkan diri sendiri. Sering kali aku menganggap enteng masalahmu. Sering kali aku menyepelekan hal-hal yang menurutmu sangat berarti.
Dan kamu adalah anak yang baik. Kamu selalu menerimaku, menemaniku. Kamu selalu sedia ketika aku mencari tempat pulang. Kamu selalu membantuku. Selalu membelaku. Selalu mau memaafkan dan memaklumi kebodohanku. Setelah aku pikir ulang, kamu adalah orang yang setelah aku sakiti, masih mau bicara baik-baik denganku. Bodohnya aku tidak memahami skala. Setiap orang punya batas, dan sepertinya kamu sudah mencapai batasmu.
Aku kembali ke ruang tamu sambil membawa secangkir kopi baru. Aku duduk dan menyalakan rokok lagi. Mengisapnya, mengembuskannya. Aku menarik rambutku dari depan ke belakang. Dan aku menyandarkan punggungku ke kursi.
“Enggak tahu,” kataku.
Itu jawabanku malam itu pada ibu. Sekarang, setelah semua telah berlalu, setelah ada jeda cukup waktu bagiku untuk memproses apa yang kurasakan, apakah aku masih menyayangimu?
Mungkin iya, pada taraf tertentu. Atau mungkin tidak, jika taraf itu tidak termasuk rasa sayang. Yang aku tahu, aku hanya tidak membencimu. Aku mencobanya, berkali-kali, tapi aku tidak bisa. Aku tidak bisa membencimu. Akan selalu ada bagian kecil dari diriku yang peduli padamu, bahkan jika itu hanya sekadar mendoakan atau mendukung dari jauh. Bagaimanapun juga aku tidak bisa menafikan bahwa kamu pernah sangat menyayangiku, dan betapa aku pernah merasa sangat dicintai.
Mungkin kamu benar, aku seharusnya bersama orang lain yang lebih baik darimu. Atau mungkin tidak perlu lebih baik, bisa saja dia lebih kekanak-kanakan, atau lebih keras kepala, atau lebih sering mengajakku bertengkar, tapi orang itu mau menerimaku, dan mau tetap bersamaku meskipun kami bertengkar sangat hebat. Kupikir aku tidak butuh orang yang lebih baik darimu. Aku hanya butuh orang yang menerimaku. Dan kuharap kamu juga menemukan orang yang kamu menerimanya.
Terima kasih telah mengajariku banyak hal. Meskipun, lagi-lagi, aku selalu lambat dalam belajar.