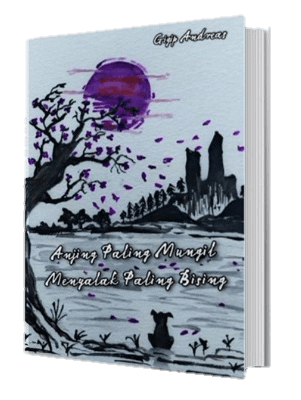Identitas buku
Judul: Kita Pergi Hari Ini
Penulis: Ziggy Zezsyazeoviennazabrizkie
Penerbit: Gramedia Pustaka Utama (2022)
Tebal: 182 halaman
“Satu hal yang tidak berubah, dan tidak akan pernah, adalah anarki total dan kekacauan. Saya tidak punya metode sama sekali. Ketika saya merasa ingin menulis cerita, saya membiarkan semuanya jatuh; saya menulis cerita.”
— Julio Cortazar
Jika desainer sampul Kita Pergi Hari Ini bertanya padaku, “Bung Gigip, berkenankah Anda memberi sepatah dua patah kata-kata mutiara untuk ditempel di buku ini?” dengan senang hati aku akan menjawab, “Dongeng terserah.”
Sedikit gambaran: buku dongeng ini bercerita tentang lima anak (lebih tepatnya empat anak bergajul plus satu bayi barbar yang suka mengumpat dan bisa menyamar jadi gerobak sate), yang bertualang bersama kucing hipster di dunia yang dipenuhi tanda-tanda kebangkitan partai idaman Karl Marx.
Anak-anak, hewan bisa bicara, politik. Apakah Ziggy ingin mempertemukan Neil Gaiman dan George Orwell? Mungkin. Terlepas dari niat pengarang, menurutku Kita Pergi Hari Ini adalah angin segar untuk sastra Indonesia karena dikemas dalam bentuk yang nyeleneh, semacam merayakan degresi dari para pendahulunya.
Agar jelas, barangkali kamu ketinggalan kabar terkini seputar sastra Indonesia, di situs web kritik sastra milik Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta, menjelang akhir tahun lalu Geger Riyanto mendefinisikan para pendahulu sebagai tulisan yang terobsesi terhadap kelirihan, kesunyian, dan keseriusan. Jadi di sini merayakan degresi adalah apa pun yang menyimpang dari ketiga obsesi tadi. (Yang sebenarnya bukan definisi baru karena sejak lama Mikael Johani sudah sering bertanya: kenapa tawa menjadi barang langka dalam sastra Indonesia?)
/1/
Aku sepakat dengan siapa pun yang mengatakan sulit untuk memisahkan bentuk dan isi dalam novel yang baik. Dalam novel yang buruk mungkin mudah karena keduanya tampak terpisah, dan itulah kenapa ia buruk. Sebagai contoh, apa yang membuat Cantik Itu Luka berhasil bukanlah karena Eka Kurniawan membangkitkan para hantu dan memasukkan unsur-unsur magis ke dalam novelnya, melainkan bagaimana cara Eka mendesain novel itu (yang kalau dipikir-pikir dipenuhi berbagai hal tak masuk akal) menjadi terasa nyata dan meyakinkan.
Di sisi lain, jamak juga novel beraliran realisme yang dari segi isi banyak berpijak pada kenyataan, tapi dari segi bentuk bisa dibilang gagal. Misalnya novel yang punya dua narator dengan POV 1 tapi suara dan cara berpikir kedua naratornya seragam (lalu untuk apa menghadirkan dua narator?), atau novel bertema kebudayaan yang penulisnya kelewat asyik membuat salinan Wikipedia (mungkin karena takut dikira kurang riset) dan mengubah bukunya jadi lebih mirip karya etnografi ketimbang prosa fiksi.
Nah, bentuk yang dipilih Ziggy untuk Kita Pergi Hari Ini, sialnya, akan lebih sering membuatmu merasa ragu alih-alih yakin. Ia seperti iseng ingin mengerjai pembacanya agar bertanya-tanya haruskah buku ini dibaca secara serius atau kuberikan ke tetangga sebelah rumahku saja? Bagaimana tidak, buku ini adalah perpaduan antara fantasi gelap dan satire politik—sebuah kombinasi yang berpotensi menghasilkan kisah epik—tapi dituturkan oleh juru dongeng yang keterlaluan bawel, sok tahu, kadang sinis kadang waras tapi seringnya tak patut dipercaya, dan ya ampun, kepalanya perlu diperiksa.
Di sepanjang cerita, dengan enteng sang narator banyak menggunakan simile yang seenak udel (kristal air menyala seperti lampu Osram; kereta air menjemput kita seperti calon menantu), deskripsi yang tak membantu (Kucing Luar Biasa adalah kucing di luar kebiasaan; Sirkus Sendu adalah sirkus tapi sendu), penokohan yang eksentrik cenderung akrobatik (Mo si bayi barbar yang belum satu tahun sangat pandai menulis esai dalam bahasa Prancis; Fifi yang baru enam tahun pernah ikut lomba renang ketika PON diadakan di Samarinda), kalimat-kalimat tak efisien, semena-mena dalam memakai huruf kapital, dan lain-lain, dan seterusnya, yang pokoknya menabrak unsur-unsur intrinsik yang akan membuat kerutan berlapis-lapis di jidat para pembaca/kritikus yang memuja efisiensi.
Tahan. Sebelum kita mencak-mencak dan menuduh Ziggy menulis sambil makan jamur tahi sapi (asumsi yang cukup akrab untuk penulis ngawur; William Faulkner sering dikira menulis sambil mabuk dan Garcia Marquez pernah dituding memakai obat bius sebelum menulis), ada satu hal yang menarik rasa penasaranku: dalam sastra Indonesia, selain Yusi Avianto lewat Raden Mandasia si Pencuri Daging Sapi, kenapa jarang ada prosa fiksi yang cara bertutur naratornya sengawur Yusi dan Ziggy? Apa karena label “sastra serius” jadi para penulisnya harus serius supaya tulisan mereka tidak diberi label “sastra bercanda”? Okelah ada banyak penulis lucu, tapi kalau cuma perkara lucu, Felix Siauw juga bisa lucu. Tapi adakah penulis “sastra serius” yang cara bertutur naratornya seganjil Sungu Lembu?
Ada, sebenarnya, dan dengan begitu ada juga jawaban dari kenapa di alinea sebelumnya. Kita bisa menyebut Dea Anugrah dan Sabda Armandio sebagai contoh. Bahkan tak cuma di sastra Indonesia, gaya bermain-main dengan degresi ini juga bisa kita jumpai di “sastra dunia”, termasuk di karya para penulis ternama—Milan Kundera dan Jose Saramago, misalnya. Tapi begini, jika cara bertutur yang dipilih Ziggy ternyata sudah banyak dipakai penulis lain, bahkan dengan bentuk yang lebih sinting, bukankah ini menjadi satu pertanyaan besar dan penting: kenapa kita jarang bertemu dengan mereka?
Aku menyebut nama-nama penulis ngawur untuk menunjukkan bahwa Ziggy bukan satu-satunya penulis yang gaya menulisnya aneh. Dan jika kita sepakat selera baca banyak dipengaruhi oleh industri (misalnya kamu marah karena para penerbit terus mencetak novel-novel Wattpad secara gila-gilaan padahal menurutmu sesuatu yang kamu sebut puisi yang kamu pajang di Blogspot itu lebih layak terbit, tapi selalu ditolak dan kamu berpikir para penerbit terlalu menuhankan duit dan pembaca lebih suka picisan dan mereka tidak mengerti puisi), apakah tidak lucu jika kita mengecap buruk sebuah buku perkara ia sukar dibaca atau bentuknya asing bagi kita, dengan dalih not my cup of tea padahal bukunya a cup of coffee?
Aha, tidak semua cangkir berisi Sariwangi, Kamerad.
/2/
Aku tak hendak mengatakan Kita Pergi Hari Ini bagus hanya karena bentuknya segar. Selain konyol, pandangan ini rawan karena, menyepakati Aan Mansyur, cenderung abai pada aspek-aspek lain yang tak kalah penting seperti: apakah karya ini rasis, seksis, atau homofobik? Apakah karya ini berpotensi memproduksi atau mereproduksi kekerasan terhadap kelompok tertentu? Kalau iya, berarti karya yang buruk. Tak peduli secanggih apa pun kemasannya, ia tetap mesti dilihat sebagai karya yang gagal secara craft.
Di luar itu, aku juga tak percaya bentuk lebih penting daripada isi. Penilaian ini seperti bilang Animal Farm keren cuma karena ia novel politik dalam kemasan fabel. Itu menyiratkan jika fabelnya dilepas, esensinya akan hilang. Ya, fabel di Animal Farm punya pengaruh, tapi lebih dari itu, yang membuatnya hebat adalah bagaimana Orwell menjitak dua sasaran kritik sekaligus: kubu kapitalis lewat Tuan Jones dan kubu komunis lewat Napoleon. Jika kita ganti semestanya jadi manusia versus ifrit, dan katakanlah judulnya jadi Kandang Dedemit, esensinya akan tetap ada, tak peduli meski kita ganti sosok Tuan Jones dengan Firaun dan Napoleon dengan siapalah-nama-ifrit-paling-seram-yang-bisa-kamu-pikirkan.
Dan itu juga berlaku untuk Kita Pergi Hari Ini. Pertama karena ia mengolok-olok berbagai isu, seperti stereotip anak laki-laki yang mesti maskulin dan perempuan yang mesti feminin (lewat Fifi dan Fufu), eksploitasi flora dan fauna (di Sirkus Sendu dan Kota Terapung Kucing Luar Biasa), krisis moneter (di Kota Suara), orang tua yang kerap bertengkar di hadapan anak-anak (saat Ma dan Fifi memeragakan sifat-sifat tercela ibu mereka), perusakan alam (uang di dasar laut diambil perompak, uang di bawah tanah diambil perampok, dan uang di ranting pohon diambil pengusaha kayu yang jahat; manusia mencemari air, menggusur tanah, membakar hutan), dan seterusnya dan sebagainya.
Kedua karena sindiran politiknya. Dalam pembacaan pertama, bagian pembukanya langsung mengingatkanku pada narasi Animal Farm (yang bukan kebetulan karena kita tahu Ziggy juga menyukai Animal Farm, paling tidak ia pernah eksplisit di Jakarta Sebelum Pagi), dan membuatku bertanya-tanya: apakah Ziggy hanya ingin menciptakan nuansa belaka atau memang berencana membuat alusi? Jawabannya bisa kita temukan di bagian ketika anak-anak bertamasya bersama Nona Gigi.
Omong-omong, meski benar Nona Gigi adalah antagonis, ia bukan villain. Jika kita mengambil jarak untuk melihat relasi antartokoh dan latar belakang mereka, posisi Nona Gigi bisa dibilang serupa Sungu Lembu (dan anak-anak adalah Raden Mandasia), hanya saja dituturkan oleh orang luar. Menarik. Butuh dua kali baca ulang sampai aku menyadari bahwa cerita ini adalah apa yang disebut “novel propaganda”.
Nilai tambah: dalam banyak novel politik yang mengusung aura distopia, cukup lazim kita temui komunisme (atau apalah yang mendekati cita-cita Marx) sebagai biang kerok dari kemerosotan dunia. Kita Pergi Hari Ini, lagi-lagi, menyimpang dari ceruk itu. Apakah Ziggy hendak berkampanye agar kita meninggalkan kapitalisme? Yang ini tak perlu dijawab dan baiknya kita segera alih topik sebelum salah satu di antara kita kepikiran mendirikan partai baru.
/3/
Kalau mau dibedah, sebenarnya struktur Kita Pergi Hari Ini cukup sederhana. Ia menggunakan struktur tiga babak pola umum, termasuk menempatkan tiap-tiap poin plot sesuai saran praktik terbaik di buku panduan menulis kreatif (yang mana saja, karena judulnya doang kreatif tapi isinya ya begitu-begitu juga). Ini keputusan bijak, sebab kalau Ziggy memakai alur maju mundur dengan struktur yang berpilin-pilin, mungkin para pembaca yang tak sabaran akan segera melempar buku ini ke luar jendela.
Tapi bukan Ziggy namanya kalau ia tidak bandel. Kendati memakai struktur yang terasa akrab bagi kebanyakan pembaca, rupanya Ziggy tak puas jika mengambil jalan yang lurus: cerita ditutup dengan poin plot akhir yang kembali ke poin plot awal di babak satu.
Kenapa Ziggy memutuskan kembali ke Imperfect World alih-alih melangkah ke Happy Ending, atau bahkan Sad Ending? Menurutku ini ada hubungannnya dengan penutup bab satu di subbab satu (yang dalam poin plot adalah gerbang menuju Point of Attack, yakni kemunculan Nona Gigi), di halaman 10.
“Karena, yang berdiri di depan mereka adalah yang selama ini mereka cari-cari:”
Kalimat ditutup bukan dengan tanda titik dan di bawahnya ada cukup ruang kosong. Ruang kosong itu, aku percaya, adalah cara Ziggy mengatakan “yang mereka cari-cari adalah ketiadaan” atau dengan kata lain, cerita ini akan berakhir dengan kesia-siaan. Aku memercayai itu karena Kita Pergi Hari Ini dibangun atas kesadaran main-main dengan (tata) bahasa seperti yang kujelaskan di awal, dan itu bukan mainan baru Ziggy.
Misalnya, para pembaca Di Tanah Lada mungkin sempat canggung dengan Ava, si bocah enam tahun tokoh utama, yang gaya bicaranya seolah ia murid Ivan Lanin. Itu bukan sekadar ingin menciptakan karakter yang nyentrik, itu memang harus dibuat begitu agar pesan yang ingin Ziggy sampaikan bisa tersampaikan. Ingat bagian ketika Ava ingin “belajar bilang enggak”? Permainan makna ganda ini adalah lelucon sekaligus pesan yang hanya bisa tersampaikan dengan desain karakter Ava yang demikian. Dan permainan bahasa, utamanya makna ganda, adalah hal yang akan sering kita temui di karya-karya Ziggy yang lain seperti Semua Ikan di Langit dan Jakarta Sebelum Pagi.
Kembali ke Kita Pergi Hari Ini. Saat kita sampai di penghujung cerita, kita bisa melihat bahwa yang kecewa di sini bukan cuma si anak-anak bergajul dan bayi barbar itu, tapi juga Bu Mo dan Ibu Tetangga Sebelah. Dan jika kita menghubungkannya dengan ruang kosong tadi, keputusan Ziggy untuk kembali ke Imperfect World bisa dibaca sebagai pesan yang mungkin ingin Ziggy sampaikan: tak peduli betapa pun dunia ini terasa mengerikan untuk anak-anak dan orang tua, baiknya terima saja karena toh, mereka tidak bisa pergi dari sini. Kita tidak bisa pergi dari dunia ini.
Sebagai penutup, sebelum menulis catatan ini, aku membaca beberapa ulasan orang lain dan menemukan Kita Pergi Hari Ini sering diberi label dongeng absurd. Oh, benarkah? Buatku tidak, Kita Pergi Hari Ini masuk akal dan cukup menggambarkan kenyataan di tempatku tinggal. Masalahnya kenyataan di tempatku tinggal memang seperti imajinasi kolektif yang dibangun oleh orang-orang absurd.